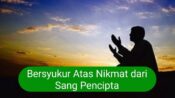Ini membuktikan bahwa pemerintah terlalu memaksakan kebijakan yang berdasarkan keinginan penguasa tidak secara evidence-based policy. Karena kebijakan yang diambil berdasarkan keinginan semata dan cenderung populis, masyarakat yang direpesentasikan dari golongan kelas menengah dirasa tidak berpihak dan berdampak secara nyata.
Akhirnya, muncullah gelombang demonstrasi yang terjadi pada akhir agustus 2025 sampai hari-hari kedepan ini yang mana dimotori oleh mahasiswa, buruh, driver ojol hingga profesional muda, bukanlah gerakan tanpa arah. Inilah yang kami sebut sebagai revolusi kelas menengah. Aksi ini sebagai akibat artikulasi dari keresahan kelas menengah yang dirasakan saat ini. Bahkan jika kita lihat lebih jauh, tuntutan aksi demonstrasi tidak lagi sekadar memperjuangkan ekonomi, tapi juga isu etika, keadilan sosial, dan masa depan demokrasi.
Masyarakat yang tergolong dalam kelas ini sudah skeptis terhadap janji-janji pembangunan yang dirasa tidak inklusif. Parahnya, para elite politik kita sering kali gagal membaca dinamika yang terjadi dimasyarakat. Pemerintah bersama elite-elite itu melihat protes ini sebagai hanya sebagai ulah anak muda yang belum paham realitas, atau sekadar keluhan kelas menengah urban semata. Padahal, jika ini diabaikan terus-menerus, keresahan ini bisa tumbuh menjadi alienasi kolektif yang jauh lebih berbahaya bagi legitimasi negara.
Saatnya Negara Mendengar
Lalu pertanyaannya sekarang adalah, jika sudah terjadi seperti ini apa yang harus dilakukan? Pertama, negara harus berhenti melihat kelas menengah hanya sebagai “pasar” atau cenderung mengaibaikan bahkan. Mereka-mereka itu adalah warga negara yang memiliki harapan terhadap tata kelola publik yang adil dan inklusif. Disini pemerintah sebagai pembuat kebijakan adalah perlu mendengarkan dan membaca gelombang ini dengan jernih. Merespons kritik mereka dengan represif atau sinis hanya akan memperparah keadaan dan memperdalam jurang ketidakpercayaan.
Kedua, disituasi saat ini akademisi dan para kaum intelektual tidak boleh lagi bersikap pasif. Sudah saatnya ruang-ruang akademik menjadi pusat pembacaan kritis terhadap fenomena ini, bukan hanya mengandalkan jargon teoretis, tetapi dengan keberpihakan pada realitas sosial yang sedang terjadi dan berubah cepat.
Ketiga, penulis memiliki pandangan bahwa posisi kelas menengah ini sebagai “penjaga moral” masyarakat. Golongan ini adalah orang-orang memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan pembangunan sosial. Sehingga kelas menengah itu sendiri pun harus terus berjuang bahkan perlu melampaui sekadar retorika moral. Harus mengambil langkah nyata, dengan memperkuat konsolidasi lintas sektor—akademisi, buruh, mahasiswa, diver ojol, jurnalis, dan profesional muda—agar terbentuk sebuah ekosistem politik yang sehat dan representatif.
Terakhir, revolusi kelas menengah yang terjadi di Indonesia saat ini bukan sebuah anomali. Ini menandai fase baru dalam relasi negara-masyarakat. Ini merupakan manifestasi dari krisis sistemik dalam demokrasi dan pembangunan kita. Jika tidak ditanggapi dengan serius, maka energi kritis ini akan membusuk menjadi sinisme. Tetapi jika dikelola dengan bijak, revolusi yang terjadi ini bisa menjadi kekuatan transformatif menuju masyarakat yang lebih adil dan demokratis.


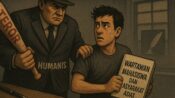
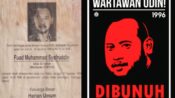
![[Opini] Paradoks Daun Sawit, Oksigen?](https://cyrustimes.com/wp-content/uploads/2025/01/Pemerhati-Lingkungan-Krismes-Santo-Haloho-M.Ling_-175x98.jpg)